“I hate social life. I hate having
it.” (Saya membenci kehidupan sosial. Saya benci
memilikinya.)
Kaget? Percayalah, itu juga reaksi
awal saya saat mendengar pengakuan seorang rekan. Apa pasal? Apakah dia tidak
suka punya teman dan lebih memilih sendirian? Apakah dia dikelilingi
orang-orang yang kurang menyenangkan, hingga lingkaran sosial jadi tampak
menakutkan di matanya?
Apakah dia hanya sosok yang egois?
Sepertinya memang lebih mudah menilainya demikian. Seperti biasa, manusia
memang palig gesit kalau perkara menghakimi – bahkan tanpa sudi mendengarkan
pihak yang mereka hakimi.
Berapa banyak dari kita yang bisa
memahami hal ini? Jangan-jangan kita cenderung lalai dan bahkan abai.
Akhirnya rekan saya bercerita:
Dulu dia punya cukup banyak
lingkaran pertemanan. Sesekali dia juga berkumpul dengan mereka, meski sisanya
lebih banyak chatting lewat BB, Whatsapp, FB, Twitter, dan lain sebagainya.
Yang lalu jadi masalah? Saat mereka
(yang mengaku teman sejati dan pengertian) mulai banyak menuntut. Sebisa
mungkin harus selalu ketemu (sesibuk apa pun.)
Oke, ada satu masa dimana rekan saya
sibuk sekali. Setiap kali diajak ketemuan, dia lebih sering tidak bisa. Rupanya
ada yang tidak terima dan reaksi mereka pun beragam. Ada yang mengeluh
terang-terangan: “Gak asik lo, sibuk
melulu!” Ada yang jadi ngambek dan malas mengajak-ajak lagi. Mungkin masih
ada yang bisa memaklumi, namun sepertinya kalah jumlah.
Lalu? Saat rekan saya akhirnya
berhasil mengusahakan waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya, bukan
sambutan menyenangkan yang dia dapat. Meski mungkin ada yang menyambutnya
dengan suka cita, tak ayal cukup banyak juga yang malah mencelanya:
“Nah,
akhirnya dateng juga lo. Diajak ketemuan susah amat, sih? Sombong amat. Sibuk
terus, ya?”
Ada
juga yang bikin kesal rekan saya: saat dia sudah berusaha meluangkan waktunya
yang kebetulan tidak banyak untuk ketemuan, yang memaksa datang ketemuan malah
dengan seenaknya datang telat... atau mendadak membatalkan acar secara sepihak!
Ada juga yang begitu datang, bukannya minta maaf karena telat, langsung ke
topik pembicaraan yang – menurut rekan saya – enggak banget: nggak jauh-jauh dari gosipin orang lain!
“Bayangin,” kata rekan saya waktu
itu, “lo udah sengaja meluangkan waktu lo yang gak sedikit, pas dateng malah
dikritik. Dikatain sombong, seolah-olah lo sengaja menghindar atau nggak mau
ketemuan sama sekali. Seakan lo yang salah karena punya kesibukan, sementara
mereka yang nggak mau ngertiin. Tapi sepertinya gue yang selalu harus ngertiin
mereka yang emang kebetulan selalu punya waktu buat kumpul bareng.”
Aduh.
Belum kelar rasa kaget saya, rekan saya melanjutkan – dengan nada sedikit
berapi-api:
“Terus, belum lagi yang suka dateng
telat. Kita semua tahu Jakarta macetnya kayak apa. Setidaknya minta maaf, kek.
Ini enggak. Udah gitu, pas mereka masih mau berlama-lama sementara waktu gue
nggak banyak dan mau pamit duluan, mereka marah dan nggak mau ngertiin. Kata
mereka: ‘Sini dulu, ngapain buru-buru?
‘Kan kita udah lama gak ketemu. Lo sibuk terus, sih. Sombong amat.’ “
Sombong.
Aih, lagi-lagi kata itu begitu mudah terucap – sama seperti suka, cinta, hingga benci.
“Trus, pas ketemuan, kirain mau
saling tukar kabar atau apa gitu.” Rekan saya masih keki luar biasa. “Eh,
taunya malah pada ngomongin orang lain. Si A begini-lah, si B begitu-lah. Si C
udah cerai dan baru kawin lagi-lah... pokoknya males banget, deh. Daripada
nanti ikutan nambah dosa, mending gue nggak usah ketemuan lagi aja sekalian.
Bukannya gue mau sok paling bener dan mutusin tali silaturahmi sih, tapi apa
gunanya gue ketemuan lagi kalo yang ada gue selalu dituduh sombong karena sibuk
dan dikatain nggak asyik? Mending mereka mau ganti bayar gaji gue kalo gue
emang lagi kena lemburan. Mending mereka sendiri seneng kalo diomongin orang
lain!”
Oke, sebelum pada keburu menuduh
rekan saya kaku, lebay, dan kelewat
sensi – mari sama-sama menilik:
Kita semua sudah tahu, persahabatan
pasti akan berubah seiring waktu. Tak ada yang abadi. Ada beda pertemanan waktu
kecil, remaja, usia 20-an, hingga 30-an ke atas. Bisa saja waktu sekelas atau
satu sekolah dulu, kita masih bisa kemana-mana bersama. Lalu mulai pisah saat
beda jadwal, beda kegiatan, dan sebagainya. Belum lagi saat pindah sekolah,
pindah kota, atau pindah ke luar negeri. Memang untung ada internet – apalagi
lewat smartphones. Cuma, rasanya
tetap beda, sih. Kita tidak selalu bisa menerjemahkan emosi lawan bicara hanya
dari SMS atau pesan di Whatsapp. Karena
itulah sering terjadi miskomunikasi yang dapat berujung konflik, meski
sebenarnya tidak perlu.
Mungkin pas masih sekampus /
sekantor, makan siang selalu bareng. Begitu salah satu pindah, frekuensi
ketemuan jadi bisa seminggu / sebulan / beberapa bulan sekali. Belum lagi
dengan pacar, teman-teman baru lainnya, dan beragam kesibukan. Apalagi bila
sudah ada yang menikah dan punya anak, sementara yang lain mungkin masih
lajang. Beda kesibukan, visi, misi, dan prioritas itu pasti. Tidak bisa
dihindari.
Masa Anda mau ngambek seperti anak
kecil, saat sahabat mendadak membatalkan acara ketemuan karena harus mengantar
anaknya yang sakit ke dokter? Anda pasti juga kesal dong, saat teman
terus-terusan memaksa Anda ketemuan, padahal saat itu Anda juga lagi
sibuk-sibuknya?
Lalu, kalau teman Anda yang semula ‘super sibuk’ itu akhirnya bisa
meluangkan waktu untuk ketemuan, berbahagialah. Tak perlu mengungkit-ungkit
yang lalu, apalagi sampai menuduhnya macam-macam. Seperti biasa, bercanda bukan
lagi bercanda bila ada hati yang sampai terluka. Sudah pada dewasa, ‘kan?
Jadilah teman yang selalu dirindukan
dan dinantikan. Caranya? Cukup belajar berlapang hati menerima realita yang
ada. Jangan terlalu risau saat teman tidak bisa selalu bertemu dengan Anda.
Tidak semua hal melulu tentang Anda.
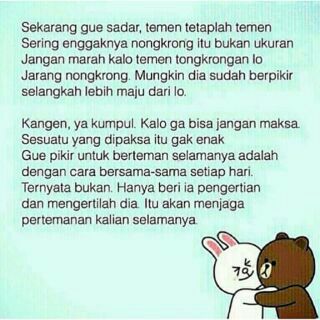
R.
(Jakarta, 27 April 2015 – 11:00 am)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar